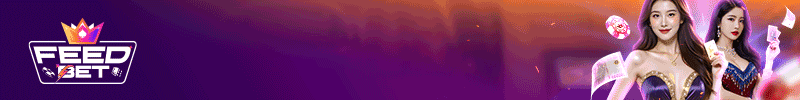Bangga! Perjalanan Jamu Hingga Diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia
jamuvoyage – Masih ingatkah Anda dengan suara denting gelas beradu dengan botol kaca—”ting, ting, ting”—yang khas dari penjual jamu gendong di pagi hari? Atau mungkin memori masa kecil Anda yang terpaksa menelan beras kencur sambil menutup hidung karena takut rasa pahit, padahal ujung-ujungnya terasa hangat dan menyegarkan? Siapa sangka, ramuan yang dulunya dianggap “kuno” dan identik dengan orang tua ini, kini telah berdiri tegak di panggung dunia.
Pada akhir tahun 2023 lalu, kabar gembira datang dari Kasane, Botswana. Dalam sesi sidang ke-18 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO secara resmi menetapkan Jamu UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dari Indonesia. Ini bukan sekadar sertifikat atau plakat pajangan, melainkan pengakuan internasional atas kearifan lokal nenek moyang kita yang telah bertahan melintasi zaman.
Coba bayangkan, ramuan yang diracik di dapur-dapur sederhana di pedesaan Jawa kini sejajar dengan Tango dari Argentina atau Yoga dari India. Penetapan ini menjadikan Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda ke-13 milik Indonesia yang diakui UNESCO. Namun, pertanyaannya adalah: mengapa dunia begitu peduli pada jamu, dan apa tanggung jawab kita setelah euforia ini mereda? Mari kita telusuri perjalanan epik “emas cair” Nusantara ini.
1. Detik-Detik Bersejarah di Botswana: Bukan Sekadar Minuman
Momen ketuk palu di Botswana pada 6 Desember 2023 menjadi titik balik. Namun, penting untuk dipahami bahwa yang diakui UNESCO bukanlah “minuman jamu”-nya semata sebagai benda mati, melainkan Jamu Wellness Culture atau Budaya Sehat Jamu.
Ini mencakup keseluruhan ekosistem: mulai dari pengetahuan para petani dalam menanam empon-empon, keterampilan para peracik (empu) dalam mengombinasikan rempah, hingga nilai sosial yang terbangun saat interaksi antara penjual jamu gendong dan pembelinya. UNESCO melihat Jamu UNESCO sebagai praktik hidup sehat yang holistik.
Fakta menariknya, UNESCO menyoroti bahwa budaya jamu mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal kesehatan dan kesejahteraan (Goal 3) serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Goal 12). Jadi, saat Anda meminum kunyit asam, Anda sebenarnya sedang berpartisipasi dalam gerakan keberlanjutan global. Keren, bukan?
2. Menelusuri Lorong Waktu: Sejarah Jamu dari Relief Candi
Jika kita bicara soal sejarah jamu, kita harus memutar waktu mundur jauh ke abad ke-8. Bukti tertua eksistensi jamu terukir abadi di dinding Candi Borobudur. Pada relief Karmawibhangga, terdapat gambaran orang yang sedang meracik obat-obatan dari tumbuhan dan memijat. Ini bukti tak terbantahkan bahwa sistem kesehatan berbasis herbal sudah mapan sejak era Kerajaan Mataram Kuno.
Kata “Jamu” sendiri diyakini berasal dari bahasa Jawa Kuno, yakni “Djampi” yang berarti penyembuhan atau doa, dan “Oesodo” yang berarti kesehatan. Jadi, secara harfiah, jamu adalah doa untuk kesehatan.
Naskah-naskah kuno seperti Serat Centhini (dipublikasikan tahun 1814) dan Serat Kawruh Bab Jampi-Jampi memuat ribuan resep jamu. Nenek moyang kita tidak meracik asal-asalan; mereka melakukan riset empiris selama ratusan tahun. Mereka tahu bahwa temulawak baik untuk hati dan jahe merah untuk menghangatkan tubuh, jauh sebelum laboratorium modern membuktikannya secara ilmiah.
3. Filosofi Keseimbangan: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati
Berbeda dengan kedokteran barat yang seringkali berfokus pada “membunuh penyakit” (kuratif), filosofi jamu lebih condong pada promotif dan preventif. Konsep dasarnya adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta keseimbangan panas dan dingin di dalam tubuh.
Inilah mengapa warisan budaya takbenda ini begitu relevan di masa kini. Di era modern yang penuh stres dan polusi, pendekatan jamu yang holistik menawarkan jalan keluar. Jamu mengajarkan kita untuk “mendengarkan” tubuh.
Misalnya, tradisi minum Cabe Puyang bagi mereka yang pegal linu bukan sekadar menghilangkan rasa sakit, tapi melancarkan peredaran darah agar tubuh bisa memulihkan dirinya sendiri. Ada unsur mindfulness dalam setiap tegukan jamu—sebuah kesadaran bahwa kita sedang memasukkan saripati alam ke dalam tubuh kita.
4. Pandemi Covid-19: Momentum Kebangkitan “Empon-Empon”
Jujur saja, sebelum pandemi, popularitas jamu sempat meredup di kalangan milenial. Jamu dianggap pahit, ribet, dan kalah gengsi dibandingkan boba tea atau kopi susu kekinian. Namun, pandemi Covid-19 mengubah segalanya.
Ingatkah Anda ketika harga jahe merah dan temulawak tiba-tiba melonjak drastis di pasar? Saat dunia panik mencari penangkal virus dan penguat imun, masyarakat Indonesia kembali menengok ke “harta karun” di dapur mereka. Istilah “empon-empon” menjadi trending topic.
Fenomena ini menjadi katalisator penting dalam penilaian UNESCO. Dunia melihat bahwa di saat krisis kesehatan global, masyarakat Indonesia memiliki ketahanan kesehatan mandiri (resiliensi) melalui budaya jamu. Jamu UNESCO bukan hanya soal tradisi masa lalu, tapi solusi relevan untuk tantangan masa kini dan masa depan.
5. Transformasi Jamu: Dari Gendong ke Cafe Kekinian
Salah satu tantangan terbesar pelestarian budaya adalah regenerasi. Jika jamu hanya berhenti di mbok gendong, mungkin ia akan punah dalam beberapa dekade lagi. Untungnya, industri jamu kini sedang mengalami revolusi yang seksi.
Sekarang, kita bisa melihat menjamurnya kafe-kafe jamu di kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Mereka menyajikan jamu dengan teknik mixology modern—dibuat sparkling, dicampur soda, atau dijadikan mocktail yang Instagramable.
Brand-brand lokal mulai mengemas jamu dalam botol kaca premium atau bentuk sachet cair yang praktis tanpa mengurangi khasiat. Inovasi ini penting agar sejarah jamu tidak terputus di generasi Z dan Alpha. Stigma “obat pahit” perlahan luntur berganti menjadi “minuman gaya hidup sehat”.
6. Dampak Ekonomi: Potensi Wisata Kebugaran (Wellness Tourism)
Pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda membuka peluang ekonomi raksasa. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa nilai pasar industri jamu dan obat tradisional terus meningkat setiap tahunnya.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat Wellness Tourism dunia, menyaingi Thailand dengan pijat tradisionalnya atau India dengan Ayurveda-nya. Wisatawan asing kini tidak hanya mencari pantai di Bali, tetapi juga pengalaman healing melalui workshop pembuatan jamu, spa rempah, dan wisata kebun tanaman obat.
Bayangkan jika setiap hotel di Indonesia menyajikan beras kencur sebagai welcome drink alih-alih jus jeruk kemasan. Dampak ekonominya bagi petani rempah dan pengrajin jamu UMKM akan sangat luar biasa.
7. Pekerjaan Rumah Kita: Melestarikan, Bukan Sekadar Membanggakan
Euforia pengakuan UNESCO memang membanggakan, tetapi ini juga membawa beban tanggung jawab. Status WBTb bisa dicabut jika negara pemiliknya gagal melestarikan budaya tersebut. Ingat, UNESCO menilai “keaktifan” budaya tersebut di tengah masyarakat.
Tantangan ke depan masih banyak. Mulai dari standardisasi kebersihan (higiene) penjual jamu tradisional, regenerasi petani tanaman obat yang kian minim, hingga perlindungan plasma nutfah tanaman asli Indonesia agar tidak dipatenkan oleh pihak asing. Kita tidak boleh sampai lengah. Jangan sampai jamu hanya menjadi komoditas ekspor, sementara anak cucu kita justru lebih akrab dengan suplemen kimia impor.
Perjalanan jamu dari relief candi kuno hingga ke ruang sidang UNESCO di Botswana adalah bukti ketangguhan budaya Nusantara. Jamu UNESCO adalah pengingat bahwa Indonesia adalah raksasa dalam hal biodiversitas dan kearifan lokal.
Jadi, sudahkah Anda minum jamu hari ini? Melestarikan jamu tidak harus dengan menjadi aktivis budaya. Cukup dengan rutin membelinya dari mbok jamu langganan atau menyeduh temulawak di rumah, Anda sudah berkontribusi menjaga napas warisan leluhur ini. Mari jadikan jamu tuan rumah di negeri sendiri dan primadona di mata dunia.